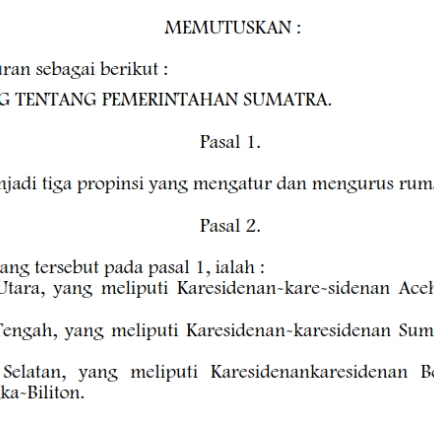Pengalamanku Masa Perang Aceh: Kesaksian Tawanan Pasukan Suami Cut Meutia (Bagian 2)
Selama dalam tawanan pasukan Teuku Chik Tunong, Karim merekam bagaimana pola perjuangan orang Aceh melawan Belanda

Atjeh Tram era penjajahan Belanda | Foto: Koleksi KITLV
Saya tiada dapat menyahut lagi.
"Nou, kau boleh jadi setoker dulu, Karem !" katanya kemudian, sedang nama saya sebetulnya Abdulkarim.
"Nanti kalau rajin dan ada jasamu, dan pengetahuanmu telah ada pula dalam hal mesin, akan segera engkau diangkat menjadi masinis. Maukah engkau dengan perjanjian itu ?"
"Dengan segala suka hati, tuan".
"Bagus!"
Saya ketika itu belum berapa bulan datang dari kampungku di Minangkabau akan mengadu nasib dinegeri sebelah utara itu. Banyak perantau pulang dari sana membawa kekayaan tiada terhingga dan sekaliannya coga-coga (bahasa Minang yang bermakna keren) kelihatan olehku. Kecongkakan mereka itu setiba dikampung menarik hatiku pula akan mengadu nasib di negeri sebelah utara itu. Esa hilang, kedua terbilang — pikir hatiku.
Kekacauan di negeri sebelah utara yang sedang menjadi-jadi itu — saya pandang sebagai air yang sedang buncah kena tuba — masa ikan berbuntangan dan orang menyauknya dengan mudah.
Telah ada dua tiga bulan saya berada di sini tapi belum juga saya beroleh pekerjaan yang menyenangkan hati. Lebih dahulu perlu saya terangkan bahwa segenap perantau dari Minang pada masa itu tiada suka memburuhkan tenaganya. Tiada sedikit juga selera mereka kejurusan itu. Dipandang “menjual diri" kepada Belanda. Terlebih-lebih karena pencaharian dalam lapangan dagang masa itu amat besar, sebentar-sebentar saja naik daun dan keuntungannya lipatganda.
Oleh sebab itu mereka coga-coga dan sangat melecehkan perburuhan.nMaka gubernemen kekurangan buruh. Baikpun dalam lapangan guru-guru, baikpun dalam pekejaan kawat dan talipun, terlebih-lebih untuk pegawai Atjeh tram. Berapa banjaknya anak Padang yang dibujuk supaya bekerja dengan gubernemen masa itu, tapi mereka tolak dengan senyum simpul, sambil menggoncangkan sakunya yang berderingan.
Mereka lebih coga berdagang di luaran. Maka jangan heran jika gaji seorang kuli jalan saja ketika itu seringgit satu hari, sedangkan harga seekor ayam cuma sepitcis dan harga sekilo beras cuma sekelip. Guru-guru hanya terambil dari orang-orang yang pandai tulis baca, habis perkara!
Dalam Atjeh tram jangan dikata lagi besar-besar gaji pegawainya! Tapi betapa keadaan saya sendiri ? Mula tiba saya coba juga berdagang seperti itu. Tapi saya ini dungu. Bukan dungu sebenarnya sebab saya tetap cerdik dan berani, hanya dungu dalam hal berdagang. Dagang apapun juga yang saja kerjakan tiada sebuah juga yang baik jalannya.
"Engkau tidak tahu di lubuknya!" kata teman-teman saya, mencela kebodohanku.
Kata lubuk itu telah jadi permainan mulut bagi mereka, yaitu tempat tersembunyi kekayaan yang bisa dikorek, serupa lubuk ikan bagi seorang penjala. Dan mereka sesungguhnya tahu di lubuknya! Dari penjual sirih atau penjaga kacang goreng, dalam sebentar saja telah melompat ke kedai nasi, dan sebentar lagi sudah mempunjai sebuah toko kain. Pandai-pandai benar mereka mencaari lubuknya!
Tapi saya tidak. Barangkali karena darah dagang tidak ada dalam tubuh saya. Saya seorang muda yang berdarah perisau. Dari semenjak kecil sudah demikian tabiatku, suka kepada pengalaman yang ganjil-ganjil, walaupun mungkin membahayakan bagi diriku sendiri. Suka benar hati saya kalau saya dapat melakukan suatu pekerjaan yang dipandang berani oleh orang dan lalu menjadi buah tutur.
Dalam kampung kami ada suatu tempat yang terkenal sangat angker, siapa yang berani melintas di situ tengah hari niscaya akan mati tegak.
Ketika itu saja masih kecil dan nakal. Benarkah? Demikian pikir saya dalam hati.
Pada suatu tengah hari tepat, sewaktu-waktu bayang-bayang tengah buntar, saya pun pergi ke situ. Teman-temanku memperhatikan dari jauh, karena tak ada seorang pun yang berani dekat. Saya menari-nari dan bersorak sorai di tempat itu, berjam-jam lamanya, sampai matahari tergelincir dari tengah. Ketika saya kembali ke kampung sampai berapa lamanya kemudian, keadaan saya tetap sehat bugar.
"Nasib baik bagi dia tidak kena tegur", kata orang mempercakapkan keberanian saya. "Kalau kena, wah, niscaya dia akan mati tegang dan tiada akan beranak lagi induknya!"
Saya hanya tersenyum saja.
Satu lagi, dalam kampung kami dahulu terkenal benar musim cindaku. Musim itu setiap bulan Haji. Kalau senja sudah turun orang tak berani lagi melangkahi tangga, dan habis magrib, biasanya segala pintu dan jendela telah terkunci. Anak-anak tidak ada lagi bermain dalam terang bulan sebagai galibnya. Tapi bagaimana dengan saya? [] (BERSAMBUNG)
Baca juga:
Pengalamanku Masa Perang Aceh: Kesaksian Tawanan Pasukan Suami Cut Meutia (Bagian 1)
Catatan:
Artikel ini adalah kesaksian dari Abdul Karim, seorang lelaki Minang yang bekerja pada Belanda sebagai penginjak rem kereta api di Atjeh Tram yang beroperasi di Lhokseumawe. Kesaksian Karim yang pernah menjadi tawanan pasukan Teungku Cut Muhammad ( suami pertama Cut Meutia) dituangkan dalam buku berjudul “Pengalamanku Masa Perang Atjeh” yang terbit tahun 1941. Dalam versi lain, buku ini diberi judul “Di Pinggir Krueng Sampoiniet” oleh Joesoef Syou’yb. Pintoe.co menurunkan kisah ini secara bersambung untuk mengenang dan mengambil hikmah dari jasa pahlawan kemerdekaan.

.jpg)